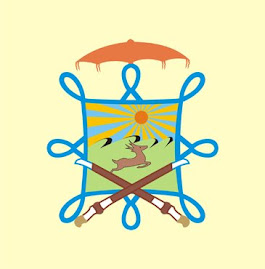Definisi KebudayaanBudaya memiliki akar kata dari bahasa Sansekerta : buddhayah. Budhayah merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan juga sering dipakai dengan istilah kultur, sebuah kata serapan dari bahasa Inggris : culture. Kata culture itu sendiri berasal dari bahasa Latin : Colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan.
Banyak definisi tentang kebudayaan yang dikemukakan para pakar. Parsudi Suparlan, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterprestasikan lingkungan dan pengalamanya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah-laku dan tindakan-tindakannya.
Lebih jauh, Parsudi Suparlan menyatakan Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.
Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya .
Sedang R. Soekmono mengatakan kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan alam penghidupan. Antropolog Koentjaraningrat berpendapat kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar .
Kebudayaan sendiri memiliki tujuh unsur yang bersifat universal. Unsur-unsur tersebut ada dan terdapat di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian .
Dengan berbagai definisi itu, maka kebudayaan bukanlah sebuah kata benda melainkan suatu kata kerja. Kebudayaan adalah karya manusia, dan tanggung jawab manusia. Demikian kebudayaan dilukiskan secara fungsional yaitu sebagai suatu relasi terhadap rencana hidup manusia. Kebudayaan kemudian tampak sebagai suatu proses belajar raksasa yang sedang dijalankan oleh umat manusia. Ini berarti perkembangan kebudayaan tidak terlaksana di luar manusia tetapi di dalam diri manusia .
Oleh sebab itu Mudji Sutrisno berpendapat, kebudayaan itu berbasis pada nilai yang mengutamakan kehidupan dan kemanusiaan. Kebudayaan merupakan ruang hidup masyarakat untuk memaknai hidup, memberi arti sosialitasnya dan identitas diri dalam upaya saling memperkaya, saling hormat dan beradab, serta adilnya kemanusiaan .
W.S. Rendra dalam Kongres Kebudayaan IV di Jakarta, 29 Oktober – 3 November 1991, mengemukakan bahwa setidaknya ada tujuh daya hidup yang harus dimiliki oleh sebuah kebudayaan. Pertama, kemampuan bernafas. Kedua, kemampuan mencerna. Ketiga, kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi. Keempat, kemampuan beradaptasi. Kelima, kemampuan mobilitas. Keenam, kemampuan tumbuh dan berkembang. Ketujuh, kemampuan regenerasi .
Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat .
Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat .
Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat .
Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat .
Dari berbagai definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kebudayaan sebagai hasil cipta, karya, dan karsa manusia merupakan pertautan antara kondisi lingkungan alam dan sosial tempat manusia tinggal dan kehendak luhur yang diharapkan. Kondisi lingkungan dan sosial tempat manusia tinggal saling pengaruh-mempengaruhi manusia baik mengenai kebiasaan, cara pandang, maupun kepercayaan.
Manusia yang hidup dalam lingkungan berpendidikan tinggi, berbeda dengan manusia dengan pendidikan rendah. Manusia yang berada di pegunungan berbeda dengan manusia yang bertempat tinggal di pantai. Manusia kota berbeda dengan manusia desa. Perbedaan melahirkan cara pandang dan tindakan serta keputusan yang berbeda. Orang berpendidikan tinggi akan berbeda cara pandang, gagasan dan tindakannya ketika menghadapi beban pekerjaan dengan manusia yang bertempat tinggal di desa. Perbedaan itu tidak bisa kemudian dilekatkan dengan ukuran kualitatif seperti baik-buruk, tinggi-rendah dan sejenisnya, melainkan dengan ukuran kepentingan atau kebutuhan. Karena perbedaan lahir dari kebutuhan yang menuntut pemenuhan. Orang desa dalam mengatasi problem pekerjaan mungkin akan memutuskan untuk membuka lahan baru atau mengubah jenis tanaman. Sedang orang kota akan melakukan dengan cara yang berbeda seperti meningkatkan produksi, mempergencar promosi dan sebagainya. Tidak bisa dikatakan membuka lahan pertanian baru lebih tinggi nilainya daripada meningkatkan produktivitas.
Dan kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi itu, keputusan yang diambil berdasarkan atas gagasan luhur yang diharapkan. Misalkan agar keturunannya dapat hidup lebih baik, agar tercipta lingkungan sosial yang harmonis dan sebagainya.
Dengan demikian kebudayaan merupakan proses yang terus-menerus berjalan, seiring dengan kemajuan yang diciptakan manusia sebelumnya. Begitu terus-menerus, dan proses tersebut tak pernah berhenti sebelum manusia meninggal. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan proses kreatif untuk memenuhi kebutuhan manusia demi menggapai gagasan luhur yang diharapkan.
Sebuah masyarakat atau suku bangsa, akan hidup dengan kebudayaannya, selama kebudayaan ‘asli’ itu dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh para pengusungnya. Namun bila tantangan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka manusia dengan kemampuannya beradaptasi, akan mencari kebudayaan lain, yang dinilai dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proses tarik-menarik tersebut sering kemudian diistilahkan dengan infiltrasi budaya asing pada budaya setempat.
Kebutuhan jelas merupakan keniscayaan hidup, oleh sebab itu kebudayaan yang tidak sanggup memenuhi tuntutan kehidupan akan ditinggalkan oleh para pengusungnya. Dan lama-kelamaan budaya setempat akan hilang sama sekali digantikan oleh kebudayaan asing. Proses tersebut melahirkan apa yang disebut kondisi ‘gegar budaya’. Gegar budaya akan membuat manusia pengusungnya akan kehilangan identitas kebudayaannya, bagai manusia tanpa rumah, ia tak memiliki hak apapun, kecuali menjalankan kewajiban yang dibebankan orang lain kepadanya.
Oleh sebab itu agar tidak terjadi “gegar budaya” diperlukan strategi kebudayaan.
Strategi Kebudayaan
Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Pengembangan kebudayaan harus dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur. Pengembangan kebudayaan juga perlu menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis, sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat merespon modernisasi dengan positif dan produktif.
Mengacu pada uraian tentang definisi kebudayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan niscaya menghendaki pembaharuan sesuai dengan etnisitas dan tradisi. Oleh sebab itu strategi kebudayaan yang harus dilakukan adalah menatap ke depan. Dalam jaman globalisasi, politik ‘pintu tertutup’ tidak lagi relevan, oleh sebab itu membangun strategi kebudayaan haruslah memiliki orientasi bahwa kebudayaan merupakan kesenyawaan antara kita dan masyarakat dunia.
Artinya ketujuh unsur kebudayaan : bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian, harus terus-menerus diperbaharui sesuai dengan perkembangan intelektual, teknologi, kondisi sosial-politik, dan tuntutan kebutuhan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa pemilik kebudayaan tersebut.
Masuknya kebudayaan asing, merupakan keniscayaan yang tak dapat ditolak, mengingat perkembangan dunia teknologi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mendorong perubahan ekonomi global. Dan perubahan ekonomi mendorong terjadinya perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat. Perubahan perilaku dan pola pikir berdampak pada kehidupan politik. Dan seringkali sikap politik yang terlembagakan akan mempengaruhi kebijakan, terutama yang secara langsung berdampak pada budaya. Misalkan dibukanya kesempatan seluas-luasnya untuk membangun perumahan, berdampak pada tanah dan perilaku masyarakat. Dibukanya lahan perkebunan komoditas tertentu untuk kepentingan industri, bisa berdampak pada hak ulayat tanah. Dan sebagainya.
Meski demikian, masuknya pengaruh dari luar yang memang tak bisa dihindarkan, tidak selalu berdampak buruk. Kemajuan teknologi informasi berdampak positip terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dapat dipergunakan untuk kepentingan produktif, misalkan dengan menciptakan alat-alat untuk membantu kehidupan.
Di samping itu kemajuan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan produk budaya. Pendokumentasian produk budaya bisa dijadikan bahan untuk melakukan dialog budaya, dari dialog budaya tersebut dapat dihasilkan sikap toleransi, kepedulian, dan hasrat untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
Dengan kata lain, segala ancaman tersebut dapat diadaptasi menjadi sebuah peluang. Kemampuan untuk mengadaptasi itu, sebenarnya sudah dimiliki oleh masing-masing kebudayaan. Hanya diperlukan cara cerdas untuk melakukan hal tersebut, agar proses adaptasi dapat berjalan dengan baik, tidak melahirkan konflik, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kebudayaan bersangkutan.
Kebudayaan Sai Batin
Kebudayaan Sai Batin di daerah Lampung Barat, terutama yang dianut oleh Paksi Pak Sekala Beghak, merupakan sebuah kebudayaan yang utuh dan lengkap. Ketujuh unsur budaya : bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian sudah dimiliki. Bahkan, berbeda dengan beberapa kebudayaan di Indonesia yang lain, kebudayaan Sai Batin, relatif masih terjaga otentisitasnya. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh letak geografis para pendukung budaya Sai Batin.
Namun agar kebudayaan tersebut dapat terus bertahan dan mampu beradaptasi dengan kebudayaan luar, diperlukan strategi yang tepat dan terencana.
Kebudayaan Sai Batin yang diusung oleh masyarakat sedarah, berasal dari leluhur yang sama, relatif mudah dikelola. Persatuan darah dan daerah menjadi perekat penting kemajuan kebudayaan Sai Batin.
Di bagian awal telah disebutkan bahwa kebudayaan dapat bertahan bila dapat memenuhi tantangan kebutuhan pengusungnya, maka kebudayaan Sai Batin juga dapat bertahan selama masyarakat adat Sai Batin dapat merasakan manfaat sebesar-besarnya kebudayaan mereka. Menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana mengubah kebudayaan dari tahap mitis-ontologis menjadi fungsional.
1. Mitis
Istilah mitis kemudian berubah menjadi mitos. Mitos berarti kisah yang memberikan pedoman dan arah tertentu untuk sekompok orang. Mitos biasanya dipelihara secara turun-temurun, dari waktu ke waktu. Kisah tersebut dapat diungkapkan dengan kata-kata, tari-tarian, atau pementasan lain, wayang misalnya. Produk budaya tersebut mengandung mitologi atau pesan tertentu yang hanya dipahami oleh pendukung kebudayaan tersebut. Dengan demikian, produk budaya menjadi sarana komunikasi, sosialisasi atau sebagai suatu proses reproduksi kebudayaan baik dalam konteks ritual, seni, maupun dalam bentuk pertunjukan lainnya. Maka mitos tidak hanya sebuah kisah masa lalu, namun memberikan arah kepada kelakuan manusia dan digunakan sebagai pedoman untuk kebijaksanaan manusia.
Mitos tersebut berfungsi sebagai : pertama, menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan-kekuatan ajaib di luar dirinya. Kedua, memberi jaminan pada masa sekarang, bahwa usaha manusia untuk mengukir sejarah hidupnya akan terus berlangsung. Dengan kata lain mitos berfungsi menampakkan kekuatan adi kodrati, menjamin kehidupan masa sekarang, memberi pemahaman bahwa manusia berada dalam lingkup kekuatan alam. Oleh sebab itu dalam alam pikiran mitis pun, manusia telah memiliki norma yang mengatur tingkah laku manusia. Norma inilah yang kemudian akan berubah menjadi lebih baik atau justru mengalami kemunduran. Norma akan berjalan sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia.
2. Ontologis
Dalam alam pikiran ontologis, manusia mulai mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang melingkupinya. Manusia berusaha memperoleh pemahaman mengenai kekuatan-kekuatan yang menggerakkan alam dan manusia. Artinya manusia mulai berpikir secara logis-rasional. Namun manusia tidak hanya berpikir secara logis-rasional saja, melainkan juga emosi dan harapan, agama dan keyakinan juga tetap berpengaruh.
3. Fungsional
Manusia tidak lagi terpesona oleh lingkungannya (mitis). Juga tidak lagi mengambil jarak terhadap obyek penelitiannya (ontologis). Tetapi manusia mulai melakukan relasi-relasi baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Dengan kata lain, tradisi yang selama ini dilihat sebagai kajian yang hanya bersifat hubungan seremoni, haruslah diaksentuasikan pada pilar-pilar baru bagi fondasi pembangunan.
Dalam konteks kebudayaan Sai Batin, sikap mitis dan ontologi, keduanya masih terus berjalan. Namun di sisi lain, kebudayaan Sai Batin perlu menjadi fungsional. Artinya bagaimana muncul hubungan antara kebudayaan dengan kepentingan pendukung kebudayaan. Bagaimana alam dan lingkungan sosial dapat dimanfaatkan untuk kepentingan para pendukungnya.
Kepentingan yang dimaksud berkaitan dengan ekonomi, politis, religi, dan identitas-kebanggaan. Kebanggaan dimaksud bukan hanya sekedar kebanggaan internal, merasa bangga menjadi anggota dari masyarakat Sai Batin, tapi juga bangga bahwa kebudayaan Sai Batin dapat memenuhi tantangan kehidupannya, dihadapan kebudayaan lain.
Sasaran yang diharapkan dari strategi tersebut adalah :
1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik intern dan antar kelompok masyarakat pendukung kebudayaan Sai Batin.
2. Semakin kokohnya kebudayaan Sai Batin, dengan filosofi dan cita-cita luhur yang diharapkan.
3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya Sai Batin.
Maka kebijakan yang dapat ditempuh adalah :
1. Mengembangkan modal sosial, berupa rasa memiliki, kebangaan, dan kepedulian.
2. Melakukan modernisasi untuk kepentingan kemajuan kebudayaan Sai Batin. Termasuk modernisasi pola pikir dan perilaku masyarakat dengan tetap menjunjung falsafah dan nilai-nilai luhur kebudayaan.
3. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas budaya Sai Batin.
4. Program Pengembangan Kekayaan Budaya yang dapat dilakukan ialah meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk budaya Sai Batin baik yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible).
Kegiatan yang akan dilakukan antara lain :
1. Transkripsi dan transliterasi naskah-naskah kuno, baik naskah dari masyarakat Sai Batin, maupun kebudayaan lain.
2. Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan antara lain peta budaya, produk-produk budaya (tarian, tambo, situs dan sebagainya)
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pendukung kebudayaan Sai Batin.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan, melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan budaya.
5. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, misalnya melalui pengadaan paket wisata, produk kerajinan dan sebagainya.
6. Bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan kekayaan budaya.
7. Melakukan dialog dengan kebudayaan-kebudayaan lain, dengan cara mengikuti pertemuan raja-raja Nusantara, melakukan kerja sama kebudayaan, pertukaran SDM yang memiliki kompetensi tertentu, dan sejenisnya.
Baca Selengkapnya...